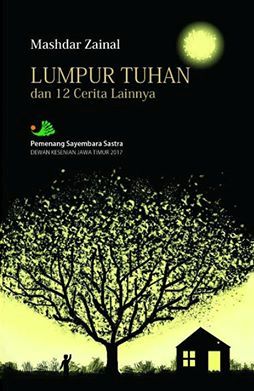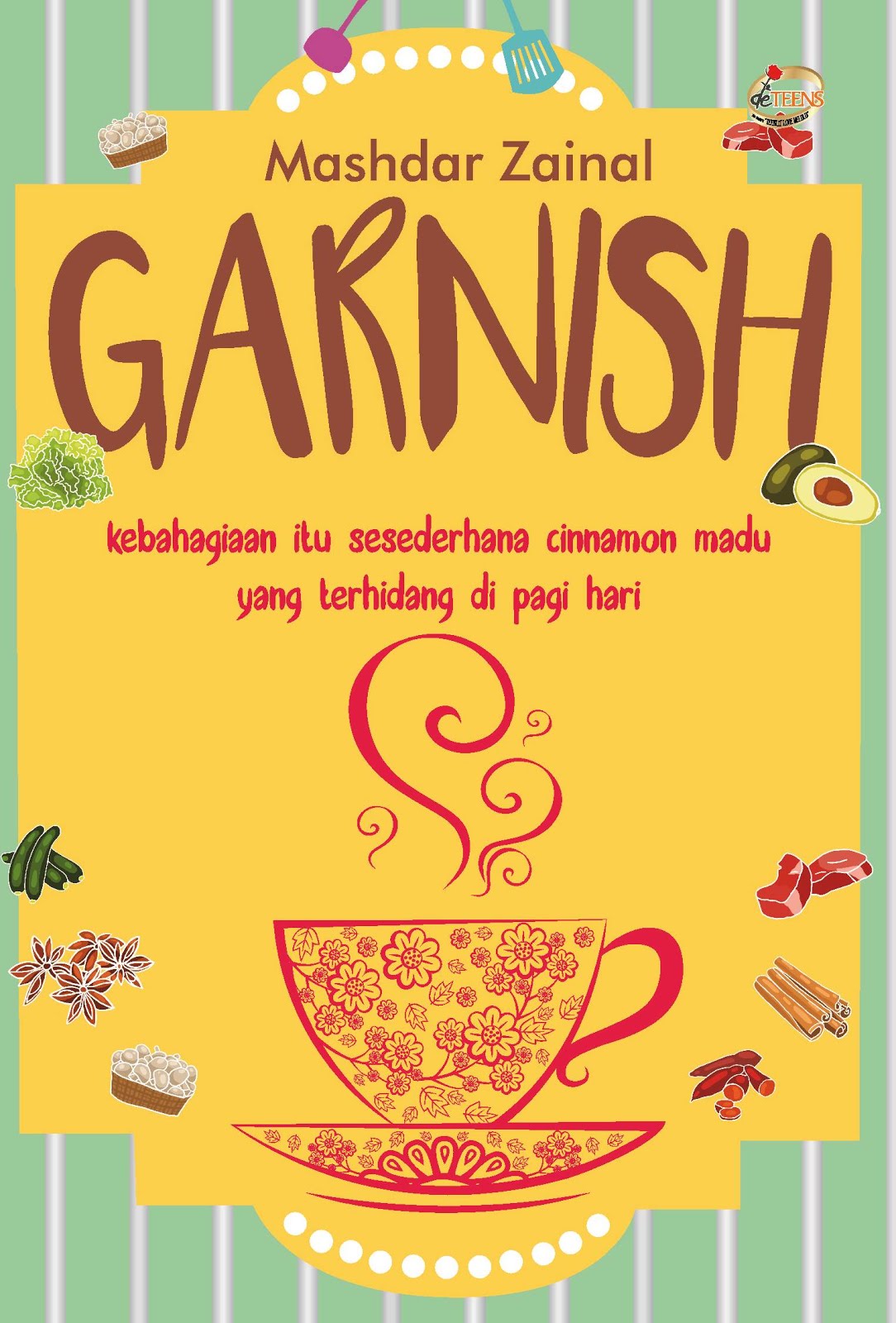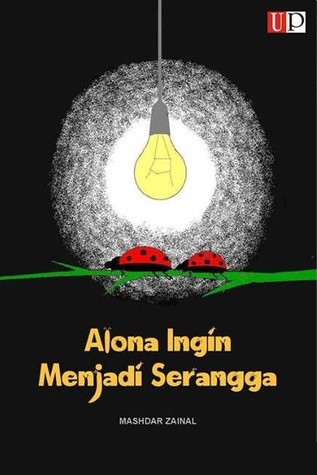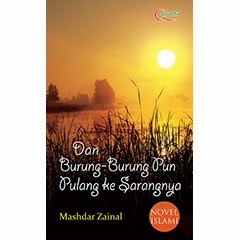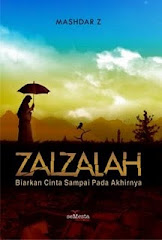Barangkali dongeng itu bermula dari halaman rumah kami—anak-anak dusun yang selalu dilelapkan sepi. Atau mungkin dari gumaman ibu-ibu yang terkantuk-kantuk menunggu anak-anaknya tertidur. Atau mungkin juga dari sebuah ladang tua yang tak terurus di pinggiran dusun, hingga ia melebat ditumbuhi dongeng-dongeng. Itu semua hanya barangkali. Mungkin. Namun, di antara kemunginan-kemungkinan itu, yang paling memungkinkan adalah: dongeng ini bermula dari sebuah malam padang mbulan, yang cahayanya selalu membanjiri kampung kami, sebulan sekali. Ya, hanya sebulan sekali. Dan malam itu, bagi kami adalah malam raya yang haram dimubazirkan.
***
Pada malam raya itu, anak-anak di dusun kami selalu menyengaja bangun. Kami membuka selimut diam-diam dan berjingkat dari ranjang. Pelan-pelan kami memutar batang kunci atau menarik grendel pintu. Tak seorang pun dari ayah atau ibu kami boleh tahu ke mana kami pergi. Kami telah membuat kesepakatan, tepat pukul dua belas malam, kami akan bertemu di sebuah ngarai kecil yang menjadi pembatas dusun dan hutan. Dari sana kami akan melakukan perjalanan malam ke sebuah ladang yang tersembunyi di bebukitan, jauh di pedalaman hutan: sebuah ladang dongeng. Kami harus bersegera, karena kami tak memliki banyak waktu. Di akhir sepertiga malam nanti, kami harus sudah kembali ke rumah masing-masing. Tidak boleh tidak. Perjalanan kami memang sedikit jauh, tapi cahaya bulan yang mengikuti langkah kami seperti sebuah kereta yang tiba-tiba mengantarkan kami ke tempat tujuan.
Sesampai di rumah petani dongeng—sebuah ladang dongeng, kami akan duduk bergerombol seperti mengitari kenduri. Kami selalu duduk dengan khusyuk dan sabar, menunggu petani dongeng memetik dongeng-dongengnya yang ranum untuk ia bagi-bagikan. Kami sangat mengagumi sosok petani dongeng, selain ramah dan dermawan, ia selalu bisa menyulap kesedihan dan keluhan kami menjadi butiran tawa, tentu saja dengan dongeng-dongengnya.
“Kalian tak perlu bersedih. Apa pula itu bersedih-sedih. Jadi, sebulan sekali kalian boleh datang ke sini. Dongeng-dongengku akan merindui kalian.” Begitulah pesan petani dongeng, setiap kami hendak berpisah. Di mata kami, petani dongeng benar-benar seperti malaikat yang diturunkan langit untuk menghibur anak-anak.
***
Mengenai perjalanannya menjadi seorang petani dongeng, ia pernah bercerita pada kami. Selalu, setiap bulan, setiap rembulan menipis menjadi segaris alis, ia mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Tepat ketika bintang-bintang mengerjap kesepian, ia berangkat tergesa-gesa untuk melakukan pengembaraan ringan ke berbagai negara di belahan dunia. Ia berangkat dengan beberapa pakaian alakadarnya, bekal makanan yang ia awetkan dalam sekaleng puisi atau cerita, tak lupa pula: kantung-kantung kecil yang ia buat dari pelepah pohon pisang kering. Kantung-kantung unik itu ia gunakan untuk menyimpan berbagai benih dongeng yang akan ia punguti dari negara-negara jauh yang akan ia singgahi, begitu katanya.
Ia berangkat dengan pesawatnya sendiri, pesawat terbang yang sayapnya bisa ia katupkan dan ia lipat dalam saku bajunya. Pesawat terbang yang bisa ia lepas-landaskan kapan saja dan di mana saja. Itulah sebabnya, perjalanannya ke berbagai belahan dunia menjadi sangat mudah dan ringan. Sudah beratus-ratus negara ia singgahi, bukan untuk relaksasi atau rekreasi, tapi semata untuk memunguti benih-benih dongeng yang hampir terlupakan. Benih-benih dongeng yang selalu bercecerean di mana-mana: di sudut-sudut kota yang ditanami gedung-gedung angkuh, di taman-taman yang penuh salju bergelantungan, di cerobong-cerobong asap yang kelam, di padang gurun yang penuh debu, di pelosok-pelosok kering yang dihuni burung nazar, dan di mana saja. Benih-benih dongeng itu, nantianya akan ia bawa pulang dan ia tanam di ladang kesayangannya, ladang dongeng paling subur yang pernah ada.
Ladang itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia miliki. Di ladang itulah ia memanen kebahagiaan lewat dongeng-dongeng yang bertunas segar dan berbunga elok. Setiap hari, tanpa lelah, ia selalu mencumbui benih-benih dongeng yang berkilauan. Ia menaburkan benih-benih dongeng itu ke gundukan tanah dengan suka cita, seperti seorang darwis yang selalu tersenyum dalam tiap jengkal tariannya. Tak lupa pula, setiap pagi ia mengguyuri lahan gemburnya itu dengan metafora yang jernih, yang seperti turun dari langit. Itulah cerita singkat tentang perjalanannya menjadi seorang petani dongeng.
***
Bila masa panen tiba, sebulan sekali, setiap purnama bugil memenuhi langit, ia selalu mengundang anak-anak kampung untuk datang ke ladangnya. Ia akan menggelar sebuah perjamuan agung, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahinya tanah dan biji-bijian yang subur. Setiap masa panen, petani dongeng selalu memanen buah yang berbeda. Kami selalu heran ketika mengenyam kenikmatan buah-buah dongeng yang tak ternamai itu.
“Mmm… Dongengmu sangat lezat, Tuan. Jika Tuan tak keberatan, berkenanlah Tuan bercerita dari mana Tuan mendapat benih-benih dongeng yang beraneka rasa ini.” Sambil mengunyah dongeng di mulut, kami selalu menyela, mengungkapkan ketakjubannya.
“Ho… jadi kalian ingin tahu?” Petani dongeng menanggapi.
“Ya!” kami menjawab serentak.
“Dunia ini mahaluas, Tuan-Puan kecil. Seperti yang pernah aku ceritakan, selepas masa panen aku selalu mengembara ke berbagai belahan dunia untuk mengutipi benih-benih dongeng yang berbeda.”
“Wah, pasti menyenangkan jalan-jalan ke negara-negara yang penuh dongeng.” Salah seorang di antara kami menyeletuk.
“Kau benar, Tuan kecil. Itu sangat menyenangkan.”
“Tuan?”
“Ya?”
“Mmm, apakah setiap negera selalu memiliki dongeng yang berbeda?”
“Ouh, tentu. Seperti buah-buah dongeng yang ada di ladang ini. Bukankah setiap bulan kita memanen buah yang berbeda.”
“Dan buah-buahnya selalu memiliki rasa yang berbeda, terkadang manis, terkadang juga masam segar, terkadang pula sedikit pedas, bahkan pernah ada yang pahit.” Salah seorang teman kami yang lain berpendapat.
“Itulah, Tuan dan Puan kecil. Setiap negera memiliki sejarahnya sendiri-sendiri. Sejarah yang perlahan akan membeku menjadi benih-benih dongeng. Dan sejarah itulah yang menentukan manis, masam, segar, pedas, atau bahkan pahitnya sebuah dongeng.”
Kami semua manggut-manggut, mendengar penjelasan dari petani dongeng.
“Mmm, lalu bagaimana caramu memunguti benih-benih dongeng itu, Tuan? Apakah seperti memunguti buah berry yang jatuh dari pohonya?”
“O, tentu tidak, Puan kecil. Benih-benih dongeng itu kukutip dengan berbagai macam cara. Aku pernah memungut benih dongeng yang terjatuh dari liur seorang raja yang tertawa, pernah pula aku memungutnya dari lidah seorang ibu yang mengantarkan tidur anaknya, dari gerai rambut seorang putri juga pernah, dari tarian aneh badut-badut, dari gumaman kamar pengantin, dari bonsai yang dikerdilkan sejarah, bahkan dari kotoran unta pun pernah.”
“Wow! Lalu, seperti apa gerangan rupa-rupa benih itu, Tuan?”
“Tunggu sebentar!” Petani dongeng mengambil sesuatu dari saku celananya.
“Apa itu, Tuan?”
“Ini namanya kantung benih!” Petani dongeng menunjukan beberapa kantung berwarna cokelat muda. Kantung indah yang terbuat dari pelepah pisang.
Beberapa detik kemudian, petani dongeng menumpahkan biji-bijian yang ada dalam kantung-kantung itu ke telapak tangannya. Butiran-butiran kecil berkilauan di telapak tangannya. Seperti manik mutiara beraneka warna. Mulut kami ternganga disihir ketakjuban. Benih-benih kecil itu benar-benar indah.
Petani dongeng mencomot satu butiran kecil dari telapak tangannya. “Yang putih tulang ini benih dongeng dari daratan Himalaya. Benih ini telah terendam salju bertahun-tahun, dan ajaibnya… benih ini masih bisa hidup.”
“Kalau yang merah pekat itu?”
“O, kalau ini saya ambil dari sebuah negeri bergurun yang penduduknya kelaparan dan menjadi santapan burung nazar. Benih itu berasal dari kotoran burung nazar.”
“Iiiih, seram.”
“Itulah dongeng, Tuan-Puan kecil. Ada yang manis ada yang pahit. Ada yang menggembirakan, ada pula yang memilukan.”
“Mmm, kalau yang bening itu?” Kami melirik biji-bijian yang ada di telapak tangan petani dongeng.
“Yang ini saya kutip dari doa seorang imam yang rela berkorban untuk rakyatnya.”
“Oooh, indah, ya. Berkilauan.”
“Tentu, jadi, kelak jika kalian menjadi seorang imam, pemimpin, jadilah imam yang rela berkorban untuk rakyatnya, memikirkan rakyatnya. Maka hidup kalian akan berkilauan.”
Kami manggut-manggut. “Nah, kalau yang hitam pekat itu?”
“Mmm, yang ini dari mana, ya? Saya agak lupa, tapi kalau tidak salah, ini saya ambil dari negeri-negeri yang rusuh. Negeri yang anarkis. Negeri yang yang penuh api.”
“Hangus ya, bijinya?”
“Begitulah. Maka dari itu, kalian jangan pernah mengumbar amarah. Amarah itu seperti api, bisa membakar apa saja. Bahkan hidup kalian bisa terbakar olehnya.”
Sekali lagi kami manggut-manggut. Malam semakin jernih. Kami terus bertanya perihal biji-bijian milik petani dongeng. Dengan sangat jeli, petani dongeng memaparkan satu demi satu sejarah biji-bijian yang ada dalam genggamannya.
Ratusan biji dongeng telah ia tanam, selalu bertunas segar dan berbunga elok, pun bila musim panen tiba, buah-buah dongeng yang ranum telah siap untuk ia petik dan ia bagi-bagikan. “Purnama ini panen kita meruah. Kalian boleh pilih sendiri, buah mana yang ingin kalian cicipi. Dongeng mana yang hendak kalian santap.”
Meski petani dongeng mempersilahkan kami untuk memilih sendiri dongeng yang kami mau, tapi kami tak pernah melakukannya. Kami selalu menyerahkan keputusan padanya. Sebagai seorang petani dongeng, tentu ia lebih tahu, dongeng yang mana yang pantas untuk kami santap.
“Banyak nian panen kita kali ini, Tuan. Menurut Tuan, buah yang mana yang sedap untuk kami santap bersama-sama?” kami berdalih, supaya ia memilihkan dongeng paling lezat buat kami santap.
Petani dongeng memicingkan matanya ke arah pohon-pohon dongeng yang rimbun dan berbuah lebat. “Emm, itu, itu! Yang itu.” Petani dongeng mendekati sebuah pohon dongeng dengan buah ranum yang bergelantungan “Nah, ini dia!”
“Buah apa itu, Tuan?”
“Buah dongeng tentu saja.”
“Aih, ini buah, buah paling elok yang pernah saya jumpai di ladangmu, Tuan.”
“Ya, buah ini memang eloknya bukan main. Dan harumnya… Hmmm!”
“Dari negeri mana Tuan dapatkan benih dongeng seelok ini?”
“Ouh, tentu saja benih ini saya ambil dari sebuah negeri yang elok pula. Negeri yang hijau dan konon gemah ripah loh jinawi. Negeri yang tanahnya sesubur tanah di ladangku ini. Negeri yang bisa menyulap togkat kayu menjadi tanaman. Negeri dengan hasil bumi dan lautnya melimpah ruah.”
“Adakah negeri yang serupa itu, Tuan? Negeri apa namanya?”
“Negeri di antah berantah yang tak kutahu namanya.”
“Wah, pasti buah ini senikmat harumnya.”
“Ayo! Tunggu apa lagi? Sini, biar saya kupas, dan lekas kita santap bersama.”
Kami berteriak kegirangan. Petani dongeng mulai menguliti buah dongeng itu perlahan. Dari mulutnya mengalun sebuah gumaman merdu. Kami sudah tak sabar menunggu. Ketika petani dongeng mulai membelah dongeng itu, tiba-tiba bau busuk menyeruak ke hidung kami. Awalnya kami mengira salah satu dari kami ada yang kentut. Tapi, tidak. Jelas sekali, bau busuk itu menyeruak dari buah dongeng yang telah terbelah di hadapan kami. Petani dongeng tercekat. Kami tercekat. Selepas dibelah, buah elok di hadapan kami tiba-tiba menghitam.
Kami membisu, menutup hidung masing-masing. Bau busuk dari buah dongeng itu semakin menyengat. Petani dongeng menatap mata kami satu persatu. Tatapan maaf yang cerlang. Dan dari cerlang matanya itu, ia seperti hendak menjelaskan, bahwa sesuatu yang indah belum tentu sempurna di dalamnya. Seperti sebuah negeri yang pernah ia singgahi. Negeri yang sangat elok, namun penuh luka dan kebusukan di dalamnya.***
Malang, Maret 2011