Semenjak bapak gemar memarahi ibu, nenek (ibu dari bapak) juga mulai gemar memarahi bapak. Dan semenjak nenek gemar memarahi bapak, bapak tak pernah lagi pulang ke rumah. Kata ibu, bapak telah berubah menjadi anjing yang dipelihara seorang perempuan muda di rumahnya.
Ibu sendiri, ia selalu sibuk dengan pekerjaan di kantornya. Maka, hanya nenek yang paling setia kuajak bermain. Nenek juga selalu tersenyum ketika aku memintanya membuatkan susu atau mie instan. Bahkan, ketika berangkat tidur, nenek masih setia menemaniku, mendongeng kelinci dan kura-kura sambil mengusap kepalaku pelan-pelan sampai aku benar-benar tertidur.
Tapi, sekarang nenek sudah tidak bisa lagi melakukan semua itu. Sudah sebulan lebih aku tak bisa bermain lagi dengan nenek. Karena, kini nenek hanya bisa terbaring lemas di kasurnya atau sesekali terduduk lesu di atas kursi roda yang didorong ibu. Ketika kutanyakan kepada ibu, apa yang terjadi dengan nenek, kenapa nenek tak bisa apa-apa lagi, ibu hanya memejamkan mata beberapa jenak, seperti tengah mengarang sebuah dongeng. Lalu setelah beberapa jenak, ibu membuka matanya yang sedikit memerah, lalu ibu mulai bercerita tentang keadaan nenek.
“Dalam tubuh nenekmu ada sebuah sungai, dan kini, sungai itu tengah dilanda kekeringan,” tutur ibu.
“Sungai?” aku memicingkan mata.
“Iya. Sungai. Sebenarnya, tubuh manusia itu adalah sebuah perkampungan. Perkampungan yang sering kali dilanda kemarau. Dan di kampung itu, di kampung itu ada sebuah sungai yang besar, sungai yang membuat penduduk kampung itu hidup.”
Aku melongo mendengarkan ibu bercerita, “Jadi dalam tubuh nenek, dalam tubuh ibu, dalam tubuhku, ada sungai yang mengalir?”
“Benar sekali.” Balas ibu mantap.
“Berarti, dalam tubuh nenek, dalam tubuh ibu, dalam tubuhku, juga ada penduduknya? Ada rumah-rumah, ada ladang, ada sawah-sawah, juga ada sungai-sungai kecil.”
“Pintar.”
“Lalu, apa yang terjadi dengan sungai nenek?”
“Seperti yang sudah ibu ceritakan, sungai di tubuh nenekmu sedang dilanda kekeringan, hampir tidak mengalir lagi.”
“Jadi, orang-orang yang ada di dalam tubuh nenek kekurangan air?”
“Bisa dibilang begitu.”
“Mereka kehausan?”
“Tentu saja. Bukan cuma itu, bahkan ladang-ladang dan persawahan pun tidak terairi lagi. Dan kau tahu, apa yang terjadi jika ladang-ladang dan persawahan itu tidak mendapatkan air? Ladang-ladang akan tandus, sawah-sawah akan kering. Lalu, padi-padi akan mati, tanaman-tanaman yang lain pun juga akan ikut mati.”
“Mmm…”
“Ya. Itulah yang terjadi pada nenekmu.”
Sekali lagi aku memicingkan mata. Memerhatikan tubuh nenek yang lunglai di atas kasur. Tubuh nenek memang tampak kering. Rambutnya yang putih merata itu tampak seperti rerumputan di tengah padang sahara. Kerontang. Bibir nenek yang biasa melantunkan cerita tampak mengelupas. Dan nenek, jelas sekali, ia mengalami banyak kesulitan. Bahkan nenek harus mengenakan pempres raksasa karena tak bisa berjalan ke kamar mandi sendiri.
Semenjak sungai di tubuh nenek mengalami kekeringan, ibu mulai meluangkan banyak waktu di rumah untuk mengurus nenek. Sesekali, budhe (kakak perempuan bapak) berkunjung untuk menjenguk nenek. Setiap kali budhe datang, budhe selalu saja menangis sambil menyebut-nyebut nama bapak dengan penuh amarah. Budhe seperti mengutuk bapak.
Budhe sendiri sebenarnya sangat sibuk, tapi ia masih sudi menyempatkan waktu untuk menjenguk nenek. Membantu ibu menyuapi nenek, menungguinya tidur, atau mengganti pempres. Aku sendiri tak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Karena, kata ibu, satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk membantu nenek adalah berdoa.
Maka diam-diam, acap kali aku menggumamkan doa supaya musim hujan dalam tubuh nenek lekas turun dan mengguyur semua yang kekeringan. Sehingga sungai di tubuh nenek lekas mengalir. Para penduduk kampung di tubuh nenek tak mengalami kekurangan air lagi. Ladang-ladang dan sawah-sawah segera terairi dan tumbuh subur lagi. Tapi, berbicara tentang para penduduk kampung, ladang-ladang, dan sawah-saah, mendadak ada hal yang ingin kutanyakan pada ibu.
“Bu,” aku menjawil lengan ibu yang tengah duduk di sebelah nenek dan menyuapinya dengan semangkuk bubur.
“Ya?” ibu menoleh sekilas.
“Kalau sungai di tubuh nenek benar-benar kering dan tidak mengalir lagi, para penduduk kampung, ladang-ladang, dan persawahan itu akan benar-benar mati, ya?”
“Begitulah.” Balas ibu sekenanya.
“Apakah itu berarti, nenek juga akan ikut mati?”
Ibu terdiam. Ia masih sibuk menyuapi nenek, seperti tidak mendengar pertanyaanku.
“Iya, Bu?”
“Iya apanya?” ibu mengelap bubur yang belepotan di bibir nenek dengan sapu tangan.
“Nenek akan benar-benar mati.”
Ketika ibu memalingkan tubuhnya ke arahku, mendadak nenek menggumamkan nama bapak berkali-kali, gumaman lirih yang tertatih-tatih. Kemudian nenek mengguncang-guncangkan tubuhnya sendiri. Hingga kepalanya melorot dari bantal. Selimut yang membaluri tubuhnya turut berantakan. Nenek terus menggumam. Gumaman yang semakin keras dan tidak jelas. Ibu hanya terdiam memandangi tubuh nenek yang seperti mengejang. Melihat mata ibu mulai memerah, aku turut terdiam.
***
Malam itu hanya ada kami bertiga di rumah. Aku, ibu, dan nenek. Malam itu tubuh nenek masih menggigil, tak henti-henti. Sesekali ia masih menggumamkan nama bapak. Aku meringkuk dalam dekapan ibu yang terkantuk-kantuk di samping dipan tempat nenek terbaring. Tiba-tiba aku merasa sangat kasihan pada ibu. Ia pasti sangat lelah mengurus nenek seorang diri. Di saat-saat seperti itu, aku membayangkan bapak ada di samping kami. Menghibur kami. Seharusnya bapak memang ada di sini, karena nenek adalah ibu dari bapak. Tapi, rasa-rasanya harapan seperti itu adalah harapan yang muspra. Karena (seperti kata ibu), bapak memang telah menjadi anjing yang dipelihara majikannya. Tak bisa keluyuran sembarangan.
“Apakah bapak benar-benar tidak akan pulang, Bu?” lirihku.
“Sudah, jangan sebut-sebut bapakmu lagi.”
“Tapi kasihan nenek, Bu, sepertinya ia kangen sama bapak.”
“Kau lihat sendiri, kepada ibunya sendiri saja bapakmu tak peduli. Apalagi pada kita. Begitulah kalau lelaki sudah menjadi anjing. Ia sudah tak peduli pada apapun melainkan pada majikannya.”
Aku mengerjap, mencoba memahami kata- kata ibu yang seperti menyimpan kesumat, “Apakah ibu tak bisa meminta kepada majikan bapak, supaya ia melepaskan bapak?”, aku kembali bertanya.
Lagi-lagi ibu terdiam. Tapi jelas sekali, mendadak, matanya memerah, sedikit air menggenang di pelupuk matanya.
“Bu?”
“Hm?” suara ibu terdengar lesu dan muram.
“Kalau memang ayah tidak mau pulang juga tidak apa-apa.”
Ibu masih membisu. Kini, ia mulai memejamkan kedua matanya yang lengket.
“Kalau ibu mengantuk, ibu tidur saja, biar aku yang menjaga nenek,” lirihku.
Ibu tersenyum, tapi matanya masih terpejam.
“Aku janji, Bu, aku tak akan mau jadi anjing siapa pun, supaya aku bisa terus menemani ibu setiap saat,” aku kembali berbisik. Ibu merapatkan dekapannya. Aku turut terdiam dalam dekapan ibu. Sepi. Sangat sepi. Nenek pun tampaknya sudah terlampau pulas. Matanya juga terpejam, meski tarikan napasnya terdengar sangat berat.
Dalam diam yang panjang itu, aku pun turut terkantuk-kantuk. Dalam kantuk itulah, aku seperti melihat tubuh nenek berubah menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan yang sangat sepi. Perkampungan yang kerontang dan mati. Di sana, aku melihat seekor anjing yang berjalan terseok-seok karena kehausan. Anjing itu mengendus tanah-tanah kering yang ia susuri, hingga ia terkapar dengan napas tersengal dan lidah menjulur-julur.
Masih dalam keadaan setengah sadar dan setengah tidur, aku bertanya-tanya, apakah anjing itu adalah bapak? ***
Malang, 5 Juli 2011


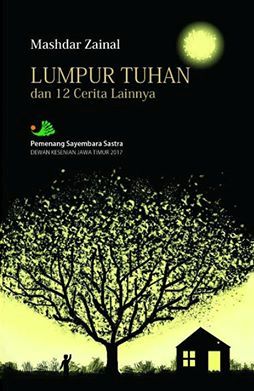
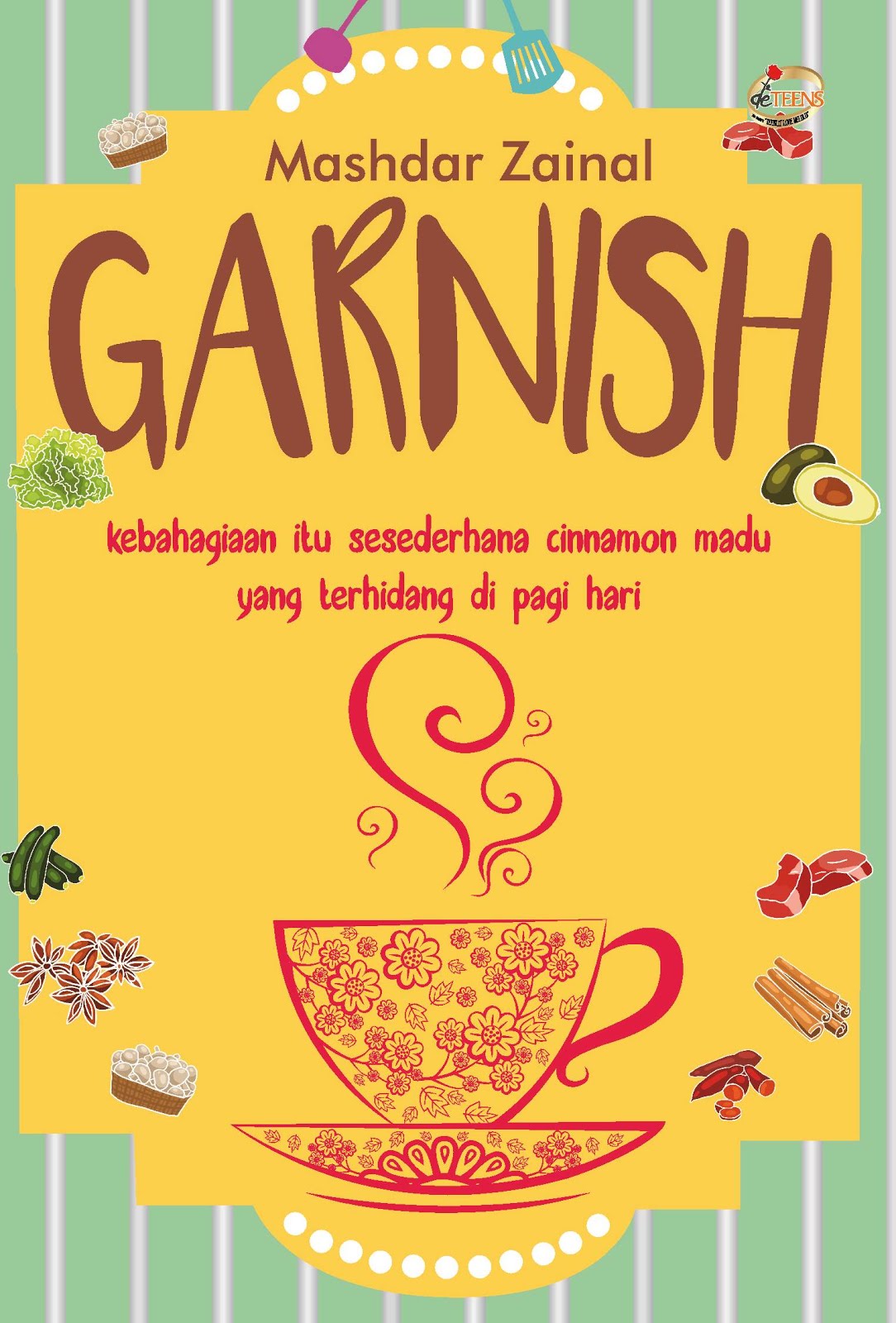
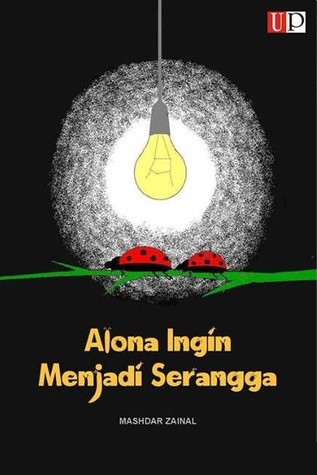
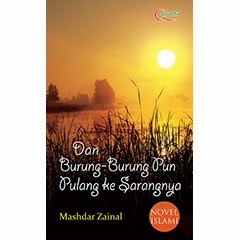


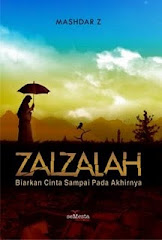



0 komentar:
Posting Komentar