Arimbi bertanya pada neneknya, mengapa hanya anak laki-laki yang gemar menerbangkan layang-layang, menarik ulur benang, seperti memainkan perasaan. Maka, sang nenek pun bercerita dan meminta Arimbi untuk membayangkan dirinya menjadi sebuah layang-layang…
***
Dan sekarang, kau adalah sebuah layang-layang yang siap dijabar terbangkan. Ketika bocah mungil itu melepas tubuhmu, kau pun mulai larung mengudara. Bertegur sapa dengan angin, sahabatmu. Berjabat erat dengan benang, kekasihmu. Kau mengenal angin dari sang alam. Bahkan, kau termazkur sebagai layang-layang juga karena angin. Tanpa angin, kau hanya sebatang bambu lidi dan kertas nahas. Lantaran angin, kau bisa mengepakkan tubuh pipihmu. Terbang. Di langit lapang. Melayang-layang. Dan begitulah kemudian mereka menyebutmu: layang-layang.
Dan sang benang, kekasihmu. Kau mengenalnya pertama kali ketika bocah kecil yang menerbangkanmu itu menalikannya dengan rusukmu. Dililitnya rusuk rapuhmu dengan pilinan ganda yang begitu kuat. Dan sejak itu, kalian bersatu. Kemana pergi. Kemana terbang. Kalian tak terpisahkan. Barangkali memang begitulah makam kekasih. Selalu ada kapan saja. Di mana saja.
Sudah suratan, sang benang akan selalu setia mendekapmu erat, bahkan ketika kau bermain terlampau jauh di ketinggian, dengan sang angin, sahabatmu. Begitulah tabiat benang, ia akan terus di sisimu hingga kemudian suratan menuliskan yang lain.
Dan sekarang, kau masih sebuah layang-layang, yang mulai mengudara. Tubuhmu naik pelan perlahan. Kau jumpai semilir. Kau hampiri sepoi. Dan kau terus melaju. Terangkat ke langit. Hamparan bumi kian mengecil. Pepohonan kian mengerdil. Dan lapangan, tempat bocah itu menerbangkanmu, menjelma kotak kecil seperti potongan cokelat. Bahkan kedua bocah yang menerbangkanmu remang menjadi titik hilang. Hanya suara mereka yang terkadang masih terdengar sayup, “Terbang, terbang. Ulurkan benangnya, ulurkan.”
Dan kau masih terus mengudara. Bersilang peluk dengan benang, kekasihmu. Kau terus mengangin. Bercurah jabat dengan siut dan siul. Lihatlah, sang benang terus memelukmu erat. Seolah tak ikhlas bila kau landas terlepas.
“Kalian benar-benar tak terpisahkan,” siut sang angin.
“Karena, bila kami berpisah, sang mautlah yang akan tandang,” balasmu, dan sang benang pun berdenting mengiyakan.
“Terima kasih sudah mengantar kami sampai cita-cita kami, di ketinggian,” desaumu.
“Sejatinya kami tak tahu bagaimana kau memandang kami,” siul sang angin, sekali lagi.
“Tentu saja kau sahabat kami, tanpamu, mustahil bagi kami untuk terbang mengudara setinggi ini.”
“Sesungguhnya kami pun masih sangsi, apakah kau terbang terbawa oleh kami, mengikuti kami, atau bahkan melawan kami.”
“Memang. Pada mulanya kami terbang karena terbawa olehmu, mengikutimu, hingga ketika kami sampai di ketinggian kami harus melawanmu. Ketika kau bersiul ke belakang, kami akan menerjang ke depan. Jika kekasihku, sang benang, tak erat memegangiku, maka bisa saja aku terlepas dan terbawa olehmu, terbang ke penjuru entah, dan berakhir entah…”
“Apa itu berarti, kami musuhmu?” Bisik semilir.
“Oh, tentu saja tidak. Kau adalah rekan bagi kami. Sekali lagi kukatakan, tanpamu, kami takkan pernah sanggup untuk terbang. Dan layang-layang yang tak pernah terbang adalah layang-layang yang tak pernah berarti apa-apa.”
“Tapi, pada kenyataannya kami acap memisahkanmu dengan kekasihmu.”
Lantas kau terdiam dalam terbangmu. Kau mulai berpikir, mungkinkah ini adil. Sejujurnya, kau sendiri gamang, apakah kau memang harus berterima kasih pada angin yang menerbangkanmu, namun terkadang juga memisahkanmu dengan kekasihmu. Atau kau, cukup berterima kasih pada benang saja, yang setia menjaga tubuhmu. Tanpa angin, kau memang tak bisa terbang. Namun, tanpa benang kau pun akan tersesat, melanglang, hilang. Sungguh, tak sanggup kau bayangkan, bagaimana ihwalmu tanpa mereka. Maka, selayaknya kau berterima kasih pada keduanya, pada angin, dan pada benang.
Dan kini, kau memilih diam dalam terbangmu, kau tak hendak menanggung perasaan yang macam-macam, lantaran, tanpa mereka (angin dan benang), kau takkan pernah berarti apa-apa. Kenyataan yang nyaris melankolia.
Dan sekarang, kau masih juga sebuah layang-layang, yang terbang melayang-layang, di ketinggian. Lepas sudah dari jangkauanmu, siapa gerangan bocah yang kini menarik ulur kekasihmu. Seperti Tuhan saja mereka, bisa mengendalikan dirimu, memperalat kekasihmu, memainkan kecemasanmu. Dan mereka, bocah-bocah yang menerbangkanmu itu, terkadang lebih mirip setan yang suka mengadu domba. Dan kini, lekas kau insyafi, bahwa segala kekacauan bermula dari ulah anak manusia. Bukan dari angin ataupun benang.
Lihatlah! Di penjuru langit, ketika musim angin tiba. Puluhan layang-layang berpesta dan mengudara. Selain terbang, layang-layang tak pernah punya cita-cita. Karena, terbang dan mengudara memang takdir mereka. Tapi, sekali lagi, bocah-bocah itu, penerbang layang-layang itu, kerap menjelma setan yang gemar mengadu domba. Setiap kali mereka melihat sepasang kekasih (layang-layang dan benang) yang lain tengah mesra mengudara, mereka takkan pernah tinggal diam. Tangan mereka gatal. Hati mereka menggerundal.
“Benangku seperti pisau, selintas saja benangmu tergesek, layang-layangmu akan tamat riwayatnya,” kata bocah yang satu.
“Yang benar saja, benangku sudah kulumuri dengan serbuk beling, hampir sehari semalam aku mengasahnya. Layang-layangmu yang bakal koit,” balas bocah yang lain.
“Kita buktikan saja.”
Dan, kekasihmu, sang benang, mulai bertaruh nyawa demi mempertahankanmu. Dan bersiaplah kau saksikan tubuh kekasihmu beradu dengan tubuh yang lain. Saling memusuhi. Saling menubruk. Saling bergesek. Saling mengiris. Saling menebas. Dan ketika waktunya tiba, akan kau simak dentingan nyaring yang diiringi siutan pilu, “Sliiiiiiiiut” itulah siutan sekarat yang menandakan bahwa leher kekasihmu telah terpenggal oleh yang lain. Dan pilinan yang selama ini menggenggammu erat akan terlepas selepas-lepasnya. Terputus seputus-putusnya. Persis seperti kepala yang terpenggal dari tubuh. Persis seperti kembang yang terpetik dari tangkai. Persis seperti layang yang terlepas dari benang, dan itu memang kau.
Dan sekarang, kau menjadi rapuh serapuh-rapuhnya. Kau diombang-ambing oleh sahabatmu sendiri, sang angin. Ke sana ke mari. Kini, kau saksikan sendiri, tanpa sang benang, angin pun hanya bisa melaksanakan titah alam. Menyeterumu. Menyeretmu. Melemparmu ke antah berantah.
Lihatlah! Kau terbang tak tentu arah. Terbolak-balik. Terjengkang. Tertampar. Terlempar. Dan kau masih terus melaju, seperti kereta tanpa cakram, seperti tubuh yang dirasuki dendam. Kau terus melayang, terombang-ambing, menubruki pucuk pepohonan, menubruki atap rumah, menubruki antenna televisi, menubruki kabel listrik, hingga akhirnya kau terantuk di pohon randu ranggas, tanpa daunan. Jasad kekasihmu yang tinggal sepenggal tersangkut di rerantingnya. Tertahan di dedahannya. Terpilin-pilin membentuk ikatan yang kuat. Ikatan yang lambat laun menjadi laknat.
Dan sekarang, kau masih layang-layang yang sendirian. Terperangkap di dahan randu yang telanjang, tanpa daunan. Kau merintih. Tanpa kekasih. Kau meratap. Tanpa sahabat. Di pohon laknat itu, kau saksikan puluhan layang-layang meregang nyawa. Tubuhnya koyak dan compang-camping oleh luka. Bahkan beberapa sudah tinggal rangka. Hatta, kau coba bertanya, “beginikah muara hidup kami?” atau “apakah ini arti lain dari terlahir untuk terbang?”, dan kau pun tak pernah menemukan jawaban.
Sang waktu pun mulai usang melampauimu. Kau hanya bisa terdiam. Dilewatii siang. Dilalui malam. Dijerang terik. Diguyur hujan. Hingga melaun tubuhmu geripis dan rentan. Sahabatmu pun, sang angin, kerap datang. Bukan untuk menjengukmu, atau pula menyelamatkanmu. Tak mungkin. Kau tahu, kedatangannya hanya untuk satu: menjemput ajalmu. Kau melihatnya. Ia datang bukan dengan semilir atau siul, tapi ia datang dengan beliung. Kau pun pasrah. Kau tak bisa menyalahkannya. Karena, ia hanya melaksanakan titah alam.
Kau tengok kembali kawan-kawanmu yang lain, yang sama-sama meregang nyawa, yang telah menjadi bangkai dan tinggal rangka. Ouh, apakah mereka pernah mencicipi cita-cita mereka: terbang. Bercinta dengan sang benang di ketinggian. Bercakap dengan sang angin di langit lapang. Ouh, bagaimana gerangan kisah hidup mereka hingga akhirnya tersangkut di sini, di tiang gantungan. Ouh, apakah mereka dihianati angin, atau sengaja ditinggalkan benang. Ataukah mereka hanya korban, sepertimu, korban adu domba. Korban kesombongan anak manusia. Ouh… tangismu robek.
Dan sekarang, kau tak mungkin mengelak. Di sini, kau seperti pesakitan yang ajalnya sudah diterakan. Kau hanya menunggu waktu. Waktu di mana, ketika tubuhmu terkoyak oleh sahabatmu sendiri. Kau tak punya pilihan. Karena kau hanya layang-layang yang dihianati angin. Layang-layang yang ditelantarkan benang. Layang-layang yang tak lagi berarti apa-apa, dan tak bisa menetukan apa-apa untuk hidupnya sendiri. Satu-satunya pilihan adalah, kau harus menikmati takdirmu.
Maka, pelan perlahan kau akan terpejam. Meresapi masa lalu dan menanggalkannya dalam butir kenangan. Simaklah! Sahabatmu, sang angin, kembali berputing sesukanya. Jasad kekasihmu yang tinggal sepenggal pun mulai berdenting. Tubuhmu pun mulai berguncang. Beberapa bagian mulai tersayat, perlahan. Sesayat demi sesayat. Secabik demi secabik. Sekoyak demi sekoyak. Kau menyimaknya, iris tangis itu, seperti masa lalu yang kau sesali kepergiannya. Kau melihatnya, luka nganga itu, seperti sumur tempat segala yang mumur dibenamkan. Sempurna dalam hilang.
Dan di ujung hayatmu, mungkin kau akan menyadari sesuatu, bahwa kekasihmu, sang benang, tak pernah sesetia itu. Karena, kini, mungkin, nun jauh di ketinggian, ia tengah berpilin dengan yang lain. Melupakanmu. Dan tak pernah kehilanganmu.
***
Arimbi memejamkan mata. Membayangkan kepiluan paling purba yang mendera layang-layang yang terputus dari benang. Kini, mungkin ia tahu, mengapa hanya anak laki-laki yang gemar menerbangkan layang-layang. Karena layang-layang adalah korban. Dan layang-layang adalah perempuan.***
Malang, Mei 2012


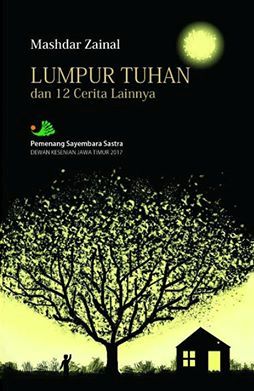
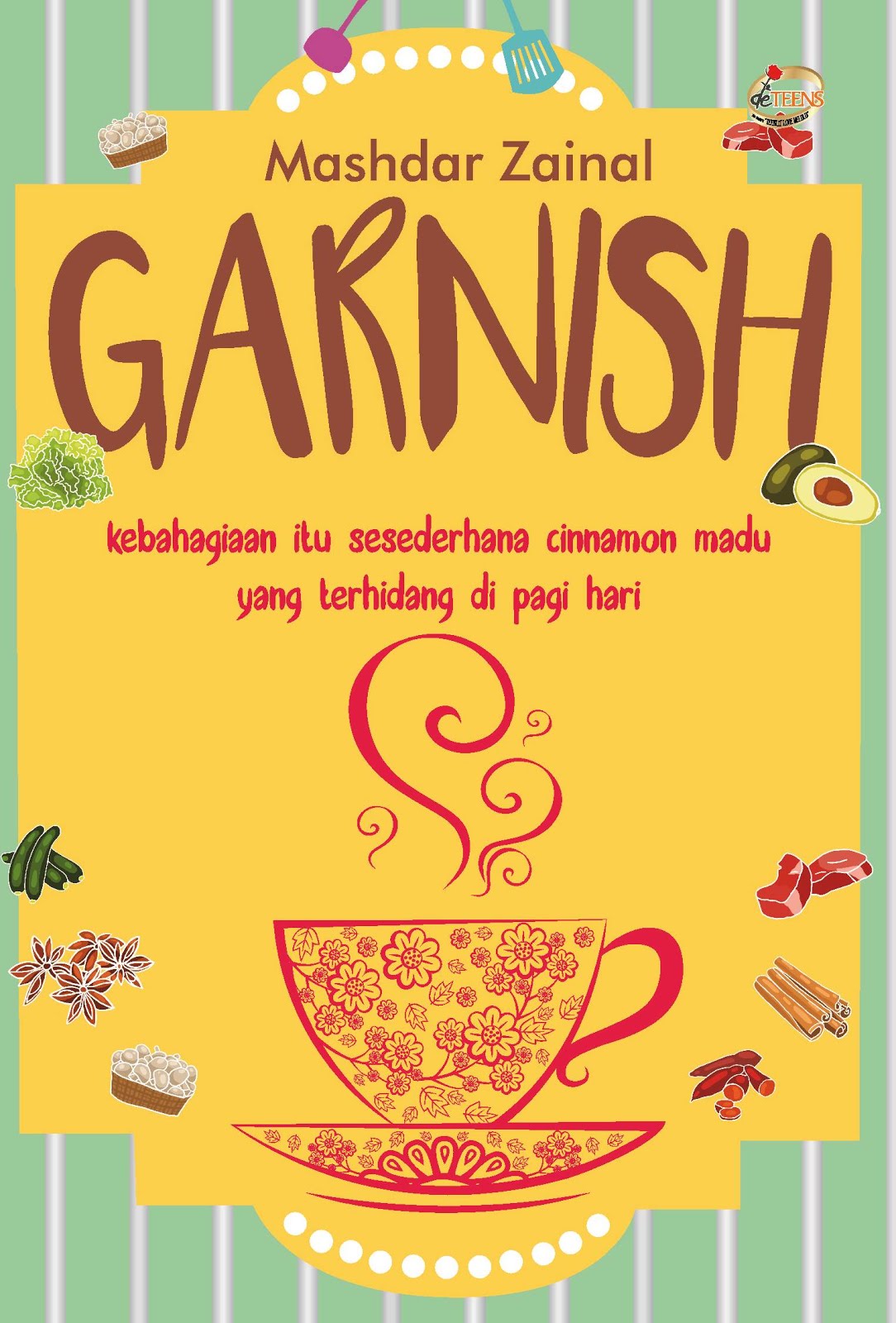
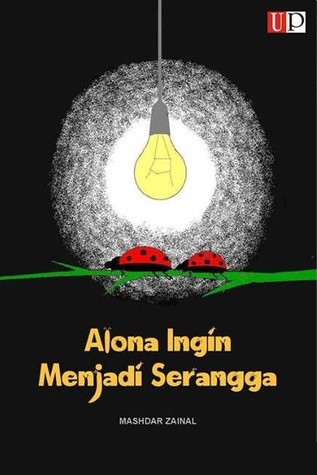
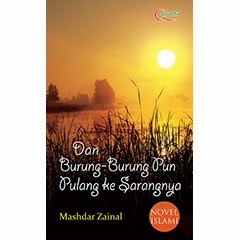


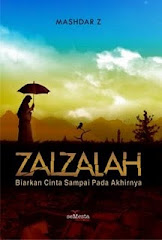



0 komentar:
Posting Komentar