Budhe baru saja meninggal,
dan rumahnya yang memiliki halaman luas itu akan segera kosong—dikosongkan, lantaran
Budhe tak punya anak ataupun pewaris yang sudi menempati rumah itu. Rumah kuno
beratap limas itu akan segera menjadi rumah tak berpenghuni, lalu anak-anak
kecil di kampung akan segera menyebutnya sebagai rumah hantu dan berlari
terbirit ketika melewati halamannya di petang hari.
Dulu, sewaktu kecil,
aku sering bermain di halaman rumah Budhe yang luas itu. Di sana tumbuh dua
pohon Angsana yang menjulang dan berjajar secara simetris, di sebelah kiri dan sebelah
kanan, hanya bersela beberapa meter saja. Bunga-bunganya yang berwarna kuning
menyala dan beraroma jeruk itu, membuat anak-anak betah bermain di bawahnya. Sewaktu
kecil, aku suka membayangkan bahwa dua pohon itu adalah sepasang kekasih yang
dikutuk menjadi pohon karena mereka terlalu mesra. Sebuah khayalan tak berdasar
yang muncul begitu saja dalam kepala mungil anak yang suka berkhayal.
Sampai
sekarang, pohon itu masih utuh dan semakin menjulang. Tubuh pohon itu semakin
kekar. Dahan dan cabangnya bersilang sengkarut bagai tangan-tangan yang
melambai dan saling berpegangan. Dan di antara dua pohon itulah, tumbuh sebuah
kisah miris tentang seorang gadis kecil yang terlunta-lunta, dan seiring waktu,
kisah miris itu telah menjulang menjadi pohon baru yang mengakar-batang dalam
ingatanku. Tak tertumbangkan.
Aku tak mengenal gadis
kecil itu dan aku tak pernah ingin mengenalnya. Kami hanya kerap bertemu di
halaman rumah Budhe, ketika ia menjajakan pecel dan opak singkongnya. Budhe
suka meneriaki gadis kecil itu untuk mampir ke beranda rumahnya bila ia tampak
lewat di halaman. Biasanya Budhe membeli dua sampai tiga pincuk pecel dan
sebungkus opak singkong darinya. Kadang-kadang Budhe juga mentraktir
kami—anak-anak yang bermain di halaman rumahnya, sebungkus opak singkong untuk
bersama.
Aku pernah mencicipi
pecel yang dibeli Budhe dari gadis kecil itu, dan rasanya sangat tidak enak,
selain kasar lumatannya, bumbu kacangnya juga terlampau asin dan pedas. Budhe
sendiri jarang menghabiskan pecel yang dibelinya, Budhe hanya meletakkan
pincuk-pincuk pecel itu di meja makan, bila seharian tak ada yang menyentuhnya,
Budhe akan melempar pecel yang hampir basi itu ke kandang ayam di belakang
rumah.
Aku pernah bertanya
pada Budhe, “Pecel itu jarang dimakan, tapi mengapa Budhe selalu membelinya,
hampir setiap hari?”
Dan Budhe hanya
tersenyum, lantas mulai bercerita perihal gadis kecil itu...
Gadis kecil itu namanya
Maryam, ia bocah yatim piatu—bapak ibunya sudah meninggal. Ia dibesarkan oleh Bibinya,
yang memiliki warung pecel di pojok pasar. Tapi begitulah, kata Budhe, Bibiya
itu adalah seorang perempuan yang judes,
suka membentak dan menyuruh-nyuruh Maryam. Orang-orang satu pasar tahu semua.
Maryam berjalan
keliling kampung, menjajakan pecel dan opak singkong itu, tidak lain juga
karena suruhan Bibinya. Maryam berjualan sepulang sekolah sampai terkadang
menjelang maghrib. Jika pecel dan opak singkongnya tidak laku, Bibinya akan
marah-marah dan terkadang memukulnya. Suatu petang, Budhe pernah mendapati
Maryam menangis sesenggukan di bawah pohon angsana di depan rumahnya. Ketika
ditanya, Maryam bilang, bahwa ia tak berani pulang, karena pecel dan opak
singkong yang dibawanya masih utuh.
Petang itu Budhe
mengantar Maryam pulang setelah membeli separuh pecel dan beberapa bungkus opak
singkong. Ketika Budhe mengantar Maryam pulang, Budhe bilang ke Bibinya, supaya
Maryam tidak usah dimarahi. Tapi begitulah, baru beberapa langkah Budhe
meninggalkan rumah itu, Budhe sudah mendengar Maryam menangis menjerit-jerit.
Dan semenjak itulah, Budhe selalu membeli pecel dan opak singkong yang
dijajakan Maryam, meski Budhe tak pernah memakannya.
Setelah mendengar
cerita dari Budhe, aku merasa sangat kasihan kepada Maryam, hingga seringkali
aku membujuk teman-teman untuk urunan membeli sebungkus opak singkong dari
Maryam.
Meski kami sudah sering
bertemu dan berpapasan, namun aku belum pernah berbicara dengannya. Maryam
memang sangat pendiam. Senyumannya pun tampak mahal. Ia hanya akan tersenyum
jika ada orang yang memanggilnya dan kemudian membeli pecel atau opak
singkongnya. Kukira ia pernah dimarahi Bibinya lantaran tidak pernah tersenyum
pada pelanggan, dan mungkin semenjak itu ia menjadi murah senyum pada setiap
pelanggan—hanya pelanggan.
Suatu hari, ketika aku
tengah bermain sepak bola bersama beberapa teman di halaman rumah Budhe, aku
telah membuat kesalahan paling fatal yang tak pernah bisa kulupakan seumur
hidup. Ketika tengah asik bermain sepak bola, aku melihat Maryam
mengendap-endap di balik pohon angsana, ia hendak lewat tapi ragu lantaran di
hadapannya beberapa bocah lelaki beringas tengah terengah-engah mengejar bola
tanpa peduli pada apapun.
Ketika aku mendapatkan bola itu, aku segera
menendangnya kuat-kuat ke arah gawang (sela di antara dua pohon angsana itulah
yang kami jadikan gawang), dengan sangat cepat bola itu meluncur ke sisian
gawang dan menghantam bakul wadah pecel yang dipanggul Maryam. Seketika bakul
wadah pecel itu pun menggelinding ke tanah, sayur dan bumbu pecel pun jatuh
berserakan berbaur dengan tanah. Seketika itu kami semua terdiam. Sementara
bola masih saja menggelinding ke luar halaman dan masuk ke dalam got.
Aku masih saja terdiam
ketika Maryam menangis sesenggukan sambil memunguti sayuran yang sudah ruah
bercampur tanah itu ke dalam bakulnya. Kami tak membantunya sama sekali. Kami
hanya bengong menontonnya. Setelah Maryam membereskan barang dagangannya yang
kacau, ia pulang dengan punggung terguncang-guncang. Kami semua hanya
meniliknya dari belakang. Beberapa saat kemudian teman-teman menudingkan jari
mereka ke arahku, semua menyalahkan aku. Detik itu aku hampir menangis, tapi
kutahan. Aku sangat menyesal karena hari itu Budhe sedang pengajian dan tak
pulang-pulang. Ketika semua teman-temanku balik ke rumah mereka masing-masing,
baru aku berjalan lesu mengambil bola yang menggelinding ke got itu dan
langsung pulang.
Aku pulang dengan wajah
merah. Bahkan ketika ibu bertanya apa yang sudah terjadi, aku tak berani
menjawabnya. Seharian itu aku terus dihantui rasa bersalah, aku terus
memikirkan bagaimana nasib Maryam. Hingga esok harinya, ketika aku bermain
kelereng di halaman rumah Budhe bersama beberapa teman, aku mendapati Maryam mengendap-endap
lagi dari balik pohon angsana. Mungkin ia marah padaku. Mungkin ia takut
padaku. Aku pura-pura tak melihatnya. Sejurus kemudian, kudengar suara Budhe
melengking memanggilnya, Maryam segera bergegas menuju beranda rumah Bude,
melewati kami, beberapa bocah lelaki yang hanya bisa menunduk dan berpura-pura sibuk
membidik kelereng-kelereng mereka.
Ketika Maryam berlalu,
aku meliriknya sekilas, dan dengan sangat jelas aku bisa melihat warna biru
lebam di pelipisnya hingga membuat matannya sedikit menyipit. Melihat itu
dadaku berdenyar cepat sekali. Seperti takut. Seperti dosa. Seperti menciut.
Seperti lara. Aku pura-pura tak melihat apa pun.
Dari kejauhan, aku
melihat Budhe tengah berbincang dengan Maryam, sesekali Budhe mengelus rambut
Maryam. Ketika mereka memalingkan wajah ke arahku, serta merta aku kembali
menunduk menekuni kelereng-kelereng di hadapanku. Setelah Maryam berlalu dari
beranda rumah Budhe, Budhe melambaikan tangan ke arahku. Aku mendatangi Budhe
dengan langkah gemetar dan ragu-ragu. Budhe mananyaiku ini-itu, dan aku malah
menangis. Satu-satunya kalimat yang keluar dari mulutku adalah, “Aku tidak
sengaja, sungguh aku tidak sengaja!”
Budhe tidak menyalahkan aku, Budhe hanya
menyesalkan diri Maryam yang lebam karena dipukuli Bibinya. Bagaimana pun aku
tetap merasa bersalah. Sangat bersalah. Dan kesalahan itu rupanya tak pernah
bisa kutebus sampai sekarang.
Setelah peristiwa itu,
pada hari-hari berikutnya, aku tak pernah berani menunjukkan muka di hadapan
Maryam. Jadi, ketika Maryam memasuki halaman rumah Budhe, aku memilih untuk
bersembunyi di balik pohon angsana sebelah kanan, sementara Maryam, ketika ia
mulai mendekati pohon angsana sebelah kiri, ia pun mulai memperlambat
langkahnya. Dari balik pohon angsana sebelah kanan, aku mengintip Maryam yang
mulai mengendap-endap, menelisik bocah-bocah yang bermain di hadapannya.
Setelah tidak mendapatiku di sana, Maryam akan berlalu dengan tenang.
Jadi begitulah, aku dan
Maryam seperti bermain kucing-kucingan di antara dua pohon angsana di halaman
rumah Budhe. Lambat laun, aku merasa bahwa yang kulakukan selama
ini—bersembunyi di balik pohon angsana, adalah salah satu hal konyol yang
pernah ada. Mungkin Maryam juga berpikir begitu. Namun, mungkin juga tidak.
Karena sampai beranjak usia remaja, Maryam masih tetap gadis yang tertutup dan
pendiam. Ia seperti seorang gadis yang hidupnya sudah terlampau kelam, tanpa
cahaya, sehingga ia lebih memilih untuk menenggelamkan dirinya lebih dalam lagi
ketimbang membuka pintu untuk dunia luar. Entahlah, kupikir tak seorang pun
tahu apa yang dipikirkan Maryam.
Begitulah, dalam
kepalaku, kehidupan Maryam tak ubahnya sebuah semak di belantara kehidupan yang
begitu luas tak beranah tepi. Hingga beberapa tahun lalu (ketika Budhe masih
hidup), Budhe berkabar bahwa kami tak akan bisa menjumpai Maryam lagi. Karena
Maryam sudah pergi menjadi TKW keluar negeri, dan meninggal di sana karena
sakit—beberapa kabar mengatakan ia meninggal karena disiksa majikkannya. Ketika
Budhe menyampaikan kabar itu, jenazah Maryam yang penuh lebam baru saja
dipulangakan. Dan Bibinya tidak menangis, melainkan menggerutu, karena harus
mengeluarkan banyak uang untuk mengurusi jenazah dan pemakaman Maryam.***
Malang,
Juni 2013


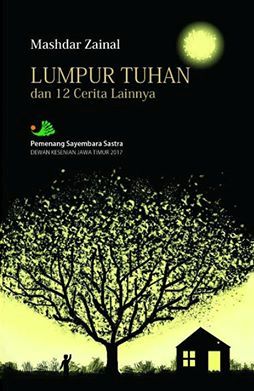
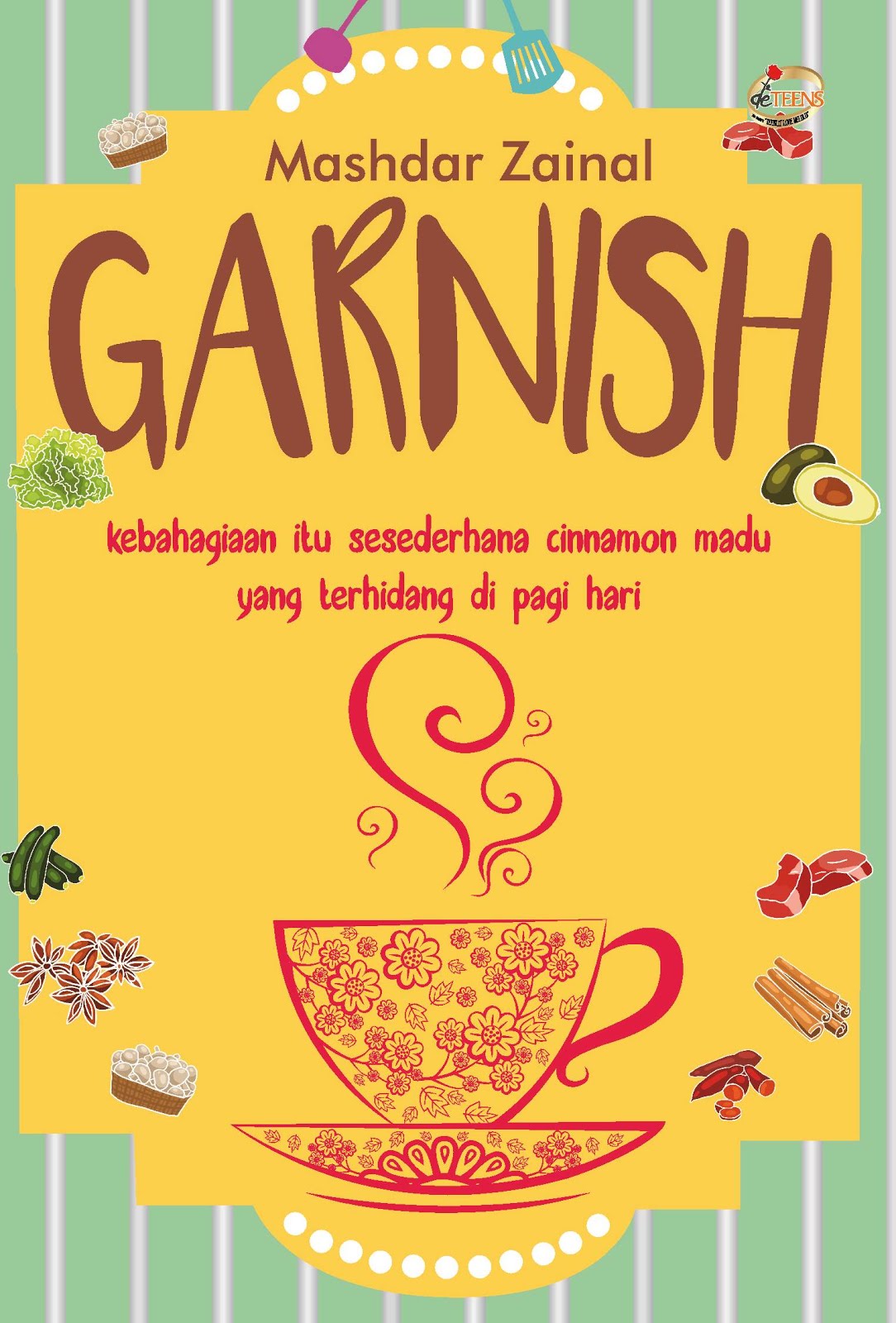
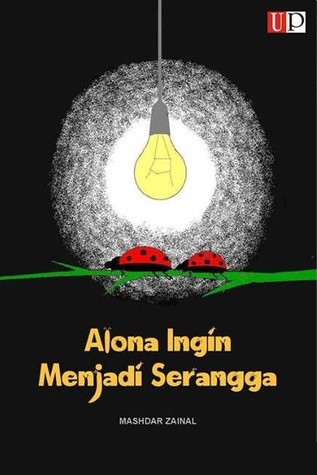
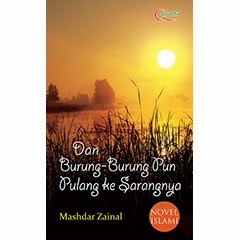


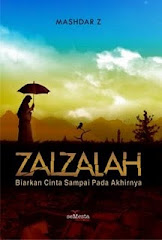



3 komentar:
Hiks, meskipun saya tidak merasa ingin kisah hidup seperti itu terbaca, tetapi begitulah kebanyakan kehidupan yang terpampang nyata. Your story has touched my heart.. :)
Thanks, sudah mampir. Semoga mencerahkan... :)
Hal ini banyak terjadi, Bang.
Posting Komentar