Semenjak
ditemukan di sebuah kebun mawar dengan tubuh penuh goresan dan nyaris telanjang,
Laluna mulai menunjukkan gejala-gejala kegilaan. Ketika itu, Mama memandikannya
dengan air hangat dan kemudian membaluti tubuhnya dengan handuk, selanjutnya Mama
menyeka bekas luka gores di sekujur tubuhnya dan mengolesinya dengan salep.
Ketika Mama hendak memakaikan pakaian, tiba-tiba Laluna berkata, “Aku tak perlu
pakaian, Ma. Aku mawar. Dan mawar tak perlu dibungkus, ia akan tetap indah dan harum.”
Ketika
itu, Mama menghentikan gerakannya dan menatap tajam ke mata Laluna, seandainya
sepasang mata Laluna itu adalah dian, maka sepasang dian itu adalah dian yang
baru saja padam, kosong, seperti jasad yang ditinggalkan ruh, “Kau bilang apa
barusan?” tanya Mama kemudian.
“Aku
hanya bilang kalau mawar itu harum, Mama. Mana bajuku,” Laluna menyahut busana
di tangan Mama dan mengenakannya sendiri.
Malam
harinya, ketika Mama mengantarkan Laluna ke kamarnya untuk istirahat, Laluna
kembali mengatakan sesuatu yang aneh, “Seharusnya tak kubiarkan para iblis itu
menusukku dengan duri-duri mereka, akulah yang mawar, duriku nyata, dan dengan
duri-duri itu aku akan mengoyak-moyak tubuh mereka, seperti yang telah mereka
lakukan padaku.”
Mama masih
tak paham dengan apa yang dibicarakan Laluna, tapi Mama sedikit khawatir
mendengar Laluna mengatakan itu, Mama menghela napas berat, “Tidurlah, Laluna,
ini sudah malam. Mama juga akan segera tidur.”
“Siapa Laluna? Aku Mawar, Ma, bukan Laluna.”
Mendengar itu, Mama mendekati Laluna yang
masih terduduk di tubir ranjang. Mama membantu Laluna membaringkan tubuhnya.
Dan sebelum Laluna memejamkan mata, ia bergumam lagi, “Seperti iblis-iblis itu,
kebanyakan lelaki memang lupa, bahwa selain indah, mawar juga berduri.”
Mama tak
ingin menyahut atau mendebatnya, setelah membenarkan letak selimut Laluna, Mama
segera beringsut ke kamarnya dengan kekhawatiran yang ia matangkan sendiri. Mama
benar-benar tak tahu apa yang terjadi dengan Laluna ketika dua hari silam ia
tidak pulang ke rumah.
Sabtu
pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Laluna berpamitan pada Mama, bahwa sepulang
sekolah ia akan langsung ke rumah sahabatnya, ketika Mama bertanya sahabat yang
mana, Laluna hanya menjawab, seorang sahabat karib yang ia kenal melalui
Facebook. Mama juga tak tahu banyak apa itu Facebook, Mama hanya pernah
mendengarnya. Laluna memang gadis yang pendiam dan hampir tak punya teman dekat.
Maka, ketika Laluna mengatakan ia punya sahabat karib, Mama tak sampai berpikir
yang macam-macam. Mama hanya senang mendengar Laluna mendapatkan sahabat karib.
Itu saja.
Selepas
pamit itulah, malamnya Laluna menelpon. Bahwa ia akan menginap di rumah sahabatnya.
Mama lega ketika Laluna mengatakan bahwa sahabatnya adalah seorang perempuan.
Dan sebenarnya, Mama tak tahu bahwa ketika itu Laluna berbohong. Yang jelas
sampai Minggu malam Laluna tidak pulang. Terakhir, Senin pagi, ketika Mama
hendak melaporkan hilangnya Laluna ke polisi, beberapa warga—yang hendak
memanen mawar di ladang mereka, menemukan Laluna tergeletak lemas di sana
dengan tubuh penuh goresan dan nyaris tanpa busana. Beberapa warga mengatakan,
bahwa Laluna telah diperkosa, sebelum akhirnya ditinggalkan begitu saja.
Hati
Mama serasa dicincang-cincang mengingat itu semua, seolah Laluna bukan manusia.
Laluna adalah anak Mama satu-satunya, dan ia diperlakukan seperti bangkai tikus
di dalam semak. Jika Mama tahu siapa yang melakukan itu, mungkin Mama akan
mematahkan leher mereka dengan tangan Mama sendiri. Beberapa orang, termasuk
Mama, sudah mendesak Laluna untuk mengatakan siapa yang melakukan perbuatan
bejat itu padanya, namun Laluna hanya diam. Seakan ia tak sanggup mengingat
kembali peristiwa itu. Hanya saja, sesekali, Laluna suka menggumam tentang tiga
iblis yang menghujani tubuhnya dengan duri-duri mereka.
“Aku
akan membalas mereka, Ma, iblis-iblis itu, Bunda Pitaya telah memberiku
kekuatan untuk itu, Mama tak perlu khawatir,” kata Laluna di suatu senja.
Mama
sudah tahu, bahwa sesuatu yang ada di dalam kepala Laluna telah rusak dan
digantikan dengan sesuatu yang lain, “Siapa Bunda Pitaya, Laluna?”
“Bunda Pitaya?
Ia adalah perempuan yang kutemui di kebun mawar, ia selalu beraroma mawar,
perempuan yang mengenakan gaun seperti jubah, gaun yang merumbai, gaun yang disulam
dari kelopak-kelopak mawar. Jika ia berjalan, ia akan meninggalkan remah-remah
mawar di setiap jejak yang ia lalui. Dialah Bunda Pitaya, Mama. Bunda Pitaya
yang jelita, Bunda Pitaya yang selalu membelaku. Dan sebenarnya, Bunda Pitaya
pernah menawariku untuk menjadikanku sebagai anaknya, tapi aku bilang, aku
harus izin Mama dulu. Aku masih anak Mama, bukan?”
Mata
Mama nyaris tak berkedip mendengar semua celotehan Laluna, anak ini benar-benar-benar
mengalami hari yang berat. Untuk mengatasi kekhawatirannya, Mama mencoba membawa
Laluna ke dokter jiwa dan psikiater, dan kata mereka, tak ada yang salah dengan
Laluna. Ia hanya mengalami trauma, ia butuh waktu untuk beristirahat dan
menjernihkan pikirannya. Itu saja.
Mama
merasa lega mendengar penjelasan dokter dan psikiater itu. Hingga beberapa hari
berselang, di kampung sebelah terjadi sebuah peristiwa yang mencengangkan. Tiga
orang pemuda yang tengah berpesta minum-muniman keras, ditemukan tewas
mengenaskan dengan mulut menganga mengeluarkan busa, selain itu di beberapa
bagian tubuh mereka ditemukan goresan memanjang, seperti bekas cakaran bintang
buas. Dan anehnya, di tempat kejadian perkara, di temukan remah-remah kelopak
mawar yang bertebaran. Sepertinya, ada seseorang yang sengaja menaburkannya.
Mendengar
peristiwa itu, mendadak Mama teringkat kata-kata Laluna tempo hari, tentang
tiga iblis yang mungkin telah menggagahinya. Dan remah-reman mawar itu? Tentang
Bunda Pitaya? Ah, mengapa semuanya tampak saling berkaitan. Mengapa pula tiba-tiba
Mama hampir mempercayai semua yang dicelotehkan Laluna. Mama menghela napas
berat sekali lagi, ia takut jika ia ikut menjadi gila karenanya.
“Aku dan
Bunda Pitaya telah mengirim mereka ke neraka, Ma, iblis-iblis itu pantas
mendapatkannya.”
Mama tak
menggurbris, tapi sesuatu di dalam hatinya terus berkerja, terus menyala, bersikejar,
bersitanya. Kian hari kondisi Laluna kian mengkhawatirkan. Ia terus meracau.
Mengatakan hal-hal yang tak terduga, hal-hal yang tak terjangkau oleh akal kepala.
Mama tak mungkin lagi menanggapinya, Mama tak akan mampu menanggapinya. Mama
hanya cukup mendengar semua ocehannya dan kemudian menyimpulkan sesuatu untuk
dirinya sendiri, sebelum mengambil sebuah keputusan untuk kebaikan Laluna.
“Ma,
apakah Mama mengizinkan jika aku menjadi anak Bunda Pitaya?”
“Ma, aku
tak mau mengenakan pakaian kalau tidak terbuat dari remah-remah mawar seperti
milik Bunda Pitaya, aku ingin menjadi jelita seperti Bunda Pitaya.”
“Ma,
Mama mencium bau mawar tidak di kamar ini? Semalam Bunda Pitaya tidur bersamaku
di kamar ini.”
“Kata
Bunda Pitaya di sini tidak aman, di sini banyak iblis yang suka menghujamkan
duri-duri mereka ke sembarang perempuan, iblis yang tak terkendalikan, maka
jika Mama mengizinkan, aku akan ikut Bunda Pitaya saja, di sana tidak ada
iblis, di sana hanya ada kebun mawar yang luas dengan keharuman yang abadi.”
“Ma,
bagaimana, Ma? Sekarang Bunda Pitaya sedang berdiri di sebelah kiri Mama.”
Mendapati
kondisi Laluna yang kian parah, Mama memutuskan untuk menyembuhkan Laluna ke tempat
yang semestinya—meski dokter dan psikiater tak menyarankan itu. Dokter dan
psikiater itu memang tak tahu apa-apa. Dan kata mereka, semua cerita Laluna yang
Mama ceritakan kembali kepada mereka tak lebih dari sebuah halusinasi yang
sebenarnya tak ada. Bagaimana pun Mama tak bisa mencegah kekhawatirannya, maka
akhirnya Mama memutuskan untuk membawa Laluna ke rumah sakit jiwa.
Pada
hari pertama, Mama menemani Laluna, dan tak beranjak dari kamarnya. Mama hanya
memastikan, bahwa selama tinggal di tempat itu, Laluna akan baik-baik saja. Dan
lagi pula, Laluna tidak menampakan gejala-gejala yang membahayakan, seperti
menyakiti orang lain, mengamuk atau merusak benda-benda yang dilihatnya.
Kegilaan Laluna hanya satu: ia seperti menyaksikan sebuah dunia yang orang lain
tak bisa menyaksikannya, dunia yang ada Bunda Pitayanya di sana, dan untuk
mengekspresikan apa yang mungkin dilihatnya, Laluna hanya meracau, tidak lebih.
“Mama
akan pulang, dan kau harus tetap di sini, kau harus sembuh,” kata Mama, sebelum
ia pergi meninggalkan Laluna.
“Aku
tidak sakit, Ma. Kalau mama pergi, meninggalkan Mawar sendirian di sini, lebih
baik Mawar ikut Bunda Pitaya saja,” balas Laluna kemudian.
Mama tak
perlu menggubris lagi kata-kata Laluna, ia memang sakit, bahkan ia masih saja
menyebut dirinya Mawar. Sebenarnya, ketika Mama beranjak pergi dari tempat itu,
air mata Mama tak mau berhenti, ia seperti mendapati dirinya menjadi kosong,
hampa. Ia merasa telah kehilangan semua yang dimilikinya. Satu-satunya harapan
yang masih ia genggam adalah Laluna bisa sembuh seperti sedia kala. Namun
harapan yang secuil itu pun turut muspra.
Pada
malam berikutnya, Mama mendapatkan kabar dari rumah sakit tempat Laluna dirawat,
kabar yang mengatakan bahwa Laluna hilang tanpa jejak. Ya, hilang begitu saja.
Bukan kabur. Karena kamar Laluna masih terkunci rapat dari luar. Utuh. Tak
tersentuh. Pun atap, dinding, dan jendela, semuanya bergeming dan tampak baik-baik
saja. Hanya saja, di kamar Laluna, Suster menemukan remah-remah mawar yang tak
terhisab jumlahnya. Remah-remah mawar yang berserak menutupi lantai, seperti
percikan darah yang terburai.***
Malang, April 2013


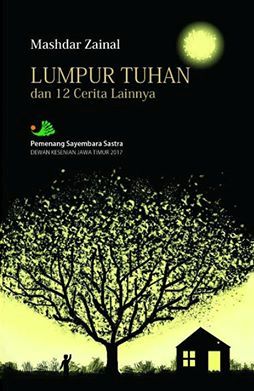
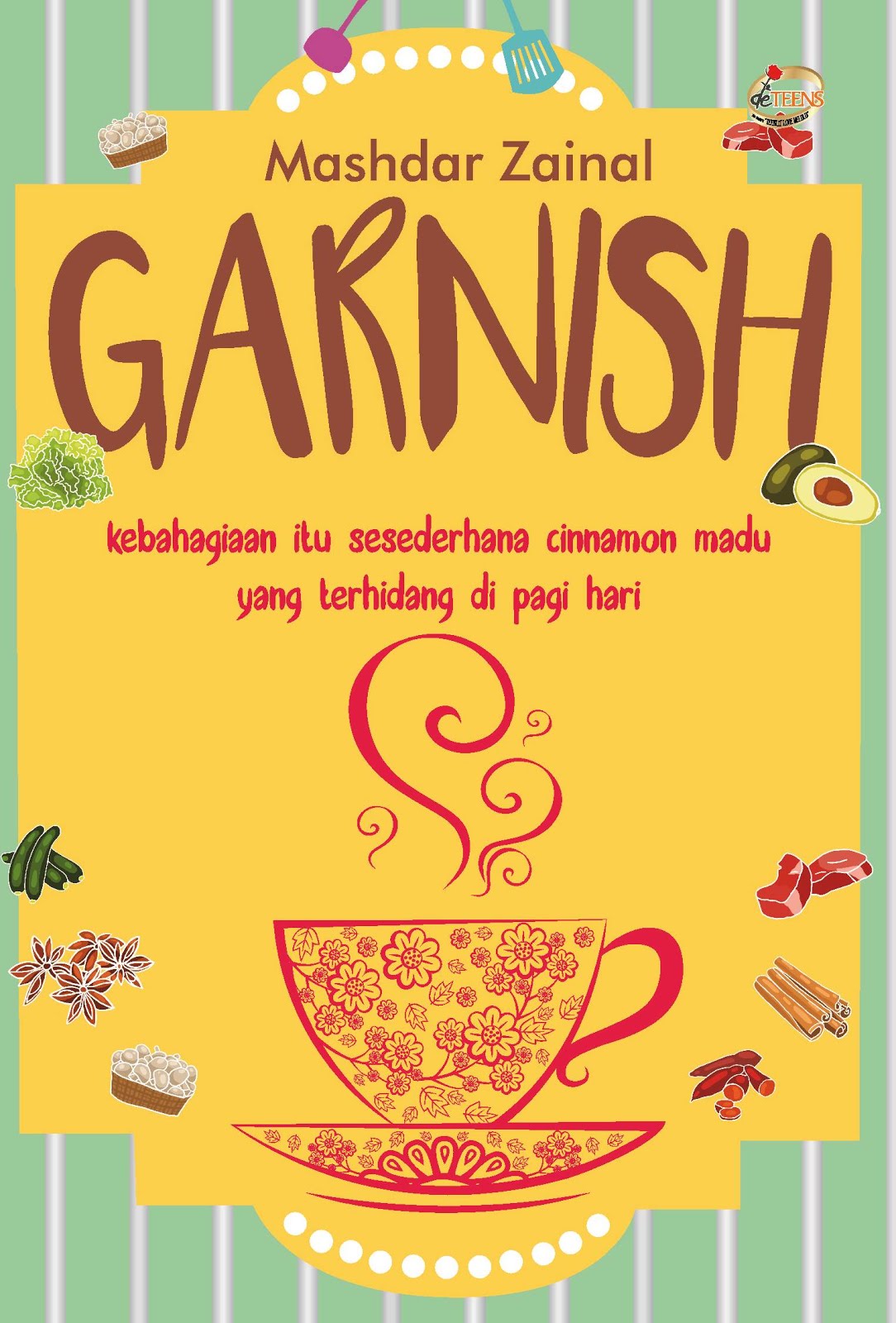
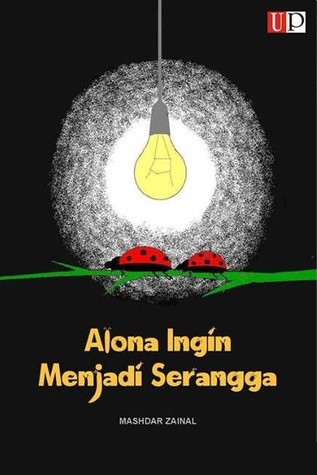
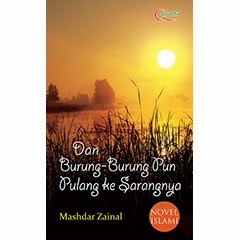


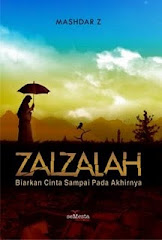



0 komentar:
Posting Komentar